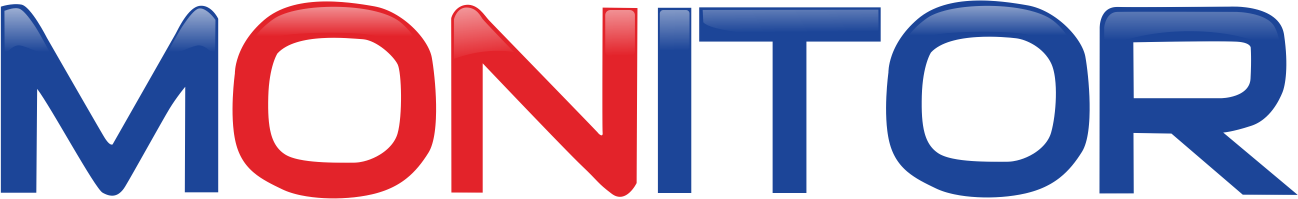Oleh: Imron Wasi
SEORANG putra kiai yang telah dibekali sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan (kognitif) keagamaan—telah sedari awal oleh ayahnya dibimbing dari hal yang terkecil: mulai dari dasar-dasar membaca hukum Al-Qur’an, nahwu-sharaf, fiqh, ushul fiqh, kitab kuning dan lainnya—yang menjadi landasan utama yang diajarkan dalam risalah pondok pesantren , terutama ponpes tradisional.
Kemudian, setelah menyelesaikan dan memahami ilmu yang telah diberikan oleh Sang Ayah, biasanya, putra kiai ini akan menempuh pendidikan keagamaan di pondok pesantren lainnya. Dengan kata lain, menimba ilmu pengetahuan kepada para kiai: baik itu di pondok pesantren yang dulu pernah menjadi tempat Sang Ayah berguru atau menimba ilmu kepada Sang Kiai—saudara/paman, dan kerabat sejawatnya yang memiliki pondok pesantren yang mempelajari nilai-nilai keagamaan yang sarat akan nilai-nilai keagamaan yang memiliki prospek akan Islam rahmatan lil ‘alamin.
Selama beberapa dekade—ia kini telah menjadi sebagai seorang santri yang berkelana dan menempuh pendidikan keagamaan di pondok pesantren yang ada di setiap pelosok desa. Ia berpindah dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren lainnya—tentunya ketika ia sudah memiliki pengetahuan yang komprehensif dan mendapatkan restu dari kiai. Selama di pondok pesantren, ia mempelajari berbagai risalah yang akan ditemuinya dalam kehidupan masyarakat sipil (civil society) dan biasanya memfokuskan salah satu bidang yang lebih dominan.
Dalam suatu pondok pesantren, seorang santri yang memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih, biasanya akan dilirik oleh Sang Kiai—lebih-lebih dipilih/atau diangkat menjadi suami dari putri kiai. Tentunya, bagi santri ini adalah suatu kehormatan yang amat mulia dan terhormat. Dan, secara praksis, saya sering mendengar kisah ini.
Nahdlatul Ulama, Santri dan Kiai
Setelah beberapa dasawarsa menempuh pendidikan di pondok pesantren, kini seorang santri itu mulai memikirkan agar bisa menyebarkan atau berdakwah keagamaan di lingkungan masyarakat pedesaan. Mula-mula, santri itu mulai mengkonstruksi langgar yang begitu sederhana. Dan, langgar yang telah usai dibuat; kini telah terisi oleh sejumlah anak-anak yang belajar bersamanya. Pada saat yang sama, ia juga membangun majlis taklim dan dibantu oleh elemen masyarakat setempat; tujuannya tentu untuk mengadakan pengajian elementer untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada awalnya, memang yang mengikuti pengajian di langgar/atau majlis taklimnya hanya segelintir orang dan cakupannya tidak begitu meluas, hanya sekitar kampung tersebut.
Namun, seiring dengan meningkatnya sejumlah santri di ponpes/majlis taklim itu, masyarakat dan anak-anak dari kampung dan desa yang berbeda pun mengikuti serangkaian pengajian itu. Kini, seorang santri itu telah menjelma menjadi seorang kiai. Ia mendapatkan legitimasi dan kepercayaan (trust) penuh dari masyarakat.
Semakin hari, santri-santri yang bertandang begitu banyak: mereka datang dari penjuru wilayah. Tak terasa, ternyata sebuah dusun itu kini sudah memiliki kiai dan pondok pesantren dengan segala keterbatasannya. Tapi, keterbatasan ini tak dijadikan sebagai alat untuk melemahkan atau mengurungkan perjuangan, justru malah meningkatkan refleksi yang kian membara untuk menciptakan transformasi dalam meningkatkan khazanah pengetahuan serta menjaga peradaban.
Begitulah keadaan realitas seorang kiai kampung yang merintis pondok pesantren dari awal tanpa melibatkan bantuan dari pemerintah. Biasanya, kiai sering dibantu oleh sejumlah santri dan sebagian besar masyarakat sekitar. Relasi antara kiai dan santri adalah dua komponen yang sangat esensial dalam sebuah entitas subkultur (pondok pesantren) dan tidak bisa dipisahkan. Sebab, keduanya memiliki hubungan yang amat kental dan inheren. Hubungan antara guru dan murid, hubungan antara pemimpin dan rakyat (santri), dan sekaligus tokoh sentral dalam dunia pendidikan keagamaan atau dalam bahasa lain dapat dikatakan adanya relasi yang bersifat patron-klien.
Bahkan, Gus Dur, pernah menyebutkan bahwa pesantren sebagai subkultur karena memiliki bangunan yang unik, terpisah dari kehidupan sekitarnya—di mana di dalam kompleks pesantren tersebut ada bangunan pengasuh, masjid, tempat pengajaran disampaikan, dan asrama sebagai tempat tinggal para santri.
Artinya, pondok pesantren itu terdiri dari kamar, gubuk, atau ruangan yang tidak begitu luas mencerminkan kebersahajaan dan kesederhanaan. Selain itu, para ustad/atau kiai yang berada di kampung—selama ini juga telah berkontribusi dan mengabdi untuk kepentingan atau jihad nasional—serta memiliki semangat yang tinggi dalam mengentaskan sejumlah pekerjaan rumah yang belum optimal diselesaikan.
Di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakstabilan—karut-marut politik transnasional dan domestik yang tak berujung pada kesejahteraan membuat keadaan menjadi tak menentu mengakibatkan sejumlah bidang terhambat—atau terhenti. Namun, selama pondok pesantren tradisional ini masih berkiprah dan menjalankan rutinitasnya dalam refleksi sosial dan menjaga dialektika pemikiran, maka tidak akan terjadi apa-apa dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki korelasi dengan ponpes tradisional dengan instrumen pertimbangan para ustad/atau kiai di ponpes tradisional didorong dan diprioritaskan serta diperhatikan secara intensif.
Dewasa ini, sejumlah tantangan besar akan dihadapi oleh para santri dan ponpes tradisional—seperti perkembangan teknologi, lingkungan, dan arus globalisasi—masyarakat industrial. Namun, tantangan lainnya, yang juga belum teratasi adalah pola pembelajaran/atau kurikulum. Biasanya, ponpes tradisional hanya dibekali ilmu yang berkenaan dengan keagamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula spirit kurikulum yang dapat sesuai dengan dinamika global tanpa menghilangkan ciri khas ponpes tradisional. Ponpes tradisional dituntut untuk responsif terhadap dinamika global, termasuk pemberdayaan ekonomi.
Selama ini, yang juga tampak menjadi kendala para santri ialah minimnya pendidikan kewirausahaan di ponpes tradisional. Sehingga, mengakibatkan kebingungan bagi para santri ketika para santri telah usai menimba ilmu. Alih-alih memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peran yang dijalankan justru belum begitu optimal.
Di sisi lain, ponpes tradisional dituntut untuk juga dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru juga mengalami kebingungan yang tak berujung dan bersifat kontradiksi dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
Meminjam perspektif cendekiawan dan intelektual, Nurcholish Madjid, salah satu masalah pokok adalah lemahnya visi dan tujuan pendirian pesantren. Menurutnya, banyak pesantren yang gagal merumuskan tujuan dan visinya dengan jelas. Ditambah lagi kegagalan menuangkan visi tersebut pada tahapan rencana kerja atau program. (Nurcholish Madjid dalam Aguk Irawan M.N, Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara, dari Era Sriwijaya sampai Pesantren Tebu Ireng dan Ploso, Pustaka IIMaN, Cetakan I, 2018: 43).
Risalah yang sudah masuk dalam ranah kurikulum perlu secara eskplisit diformulasikan secara spesifik, agar khazanah ilmu pengetahuan yang selama ini diajarkan di ponpes tradisional, mengalami transformasi secara perlahan yang akan bermuara pada transmisi pengetahuan yang terarah/atau terukur.
Para ustad/kiai kampunglah yang seyogianya mengukuhkan nilai-nilai yang selaras dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya NU memberikan edukasi secara merata, total dan holistik. Agar keberadaan para ustad/kiai yang selama ini tinggal di pedesaan pula merasa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Bukan hanya sebatas yang sering ditunjukkan oleh kita—terlebih pemimpin NU—bahwa ponpes tradisional di pedesaan adalah bagian dari NU. Tapi, program yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dikembangkan sampai ke tingkat akar rumput (grass roots). Sehingga, mengakibatkan ketidakpedulian dan tidak ambil pusing terhadap representasi kader/atau jam’iyah NU di dalam struktur lembaga negara dan birokrasi.
Terlepas dari itu semua, ada sesuatu kekhawatiran yang selama ini merambah pikiran ialah apabila adanya keterlibatan sejumlah petinggi dalam ruang lingkup politik praktis—lebih-lebih menjadi pengurus partai politik. Selain itu, agenda janga panjang yang selama ini sudah tertanam dalam cita-cita nasional semakin mulai terkikis dan tertimpa dengan sibuknya mencari dan mengejar proyek dan jabatan, berlalu-lalang bak selebritis yang tampil di media massa, sibuk menjadi broker politik, timses, dan yang lebih parah adalah menjajakan NU sebagai komoditi politik. Meskipun, tidak bisa dinafikan bahwa setiap warga negara memiliki haknya dalam bersikap, terutama dalam politik.
Terakhir, umat perlu kembali kepada cita-cita awal—menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan hasil konsensus yang telah termaktub dalam misi nasional. Dan, terpilihnya sejumlah representasi umat Muslim—terutama warga NU dapat membawa perubahan dan membuat skema orientasi yang terukur serta mewujudkan kepentingan umat. Perhatian terhadap pondok pesantren tradisonal perlu secara masif diaktualisasikan untuk menciptakan dan membangun ekonomi dan pemberdayaan umat, termasuk masyarakat.
Selama ini, menurut sejarawan dan sastrawan, Kuntowijoyo (2018:267), yang mengemukakan bahwa dalam politik umat Islam seperti pemumpang perahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang tanpa kompas, tidak tahu tujuan , dan tidak tahu cara berlayar. (Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, IRCiSoD, cetakan pertama, 2018: 267).
Oleh karena itu, orientasi jangka panjang semestinya segera diwujudkan dalam rencana/atau program prioritas dengan menjadikan pondok pesantren sebagai episentrum peradaban. Dengan demikian, hadirnya regulasi mengenai pondok pesantren diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan umat secara umum, dan ustad/kiai dan ponpes tradisional pada khususnya. Dalam upaya mengatasi tantangan yang akan dihadapi memang membutuhkan semua komponen: baik itu organisasi masyarakat, pemerintah, masyarakat, dan institusi/atau forum-forum pondok pesantren. Pada dasarnya, secara praksis memang ponpes juga identik dengan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Dengan demikian, perlu sinergitas dan kerja sama di antara berbagai elemen untuk menumbuhkan dan mewujudkan cita-cita agama dan bangsa. Pada tulisan yang telah dibahas di atas, penulis membatasinya, bukan bermaksud memberikan dikotomi.
*Penulis adalah Mantan Wakil Presiden Mahasiswa dan Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi, kini terlibat aktif di Banten Institute for Governance Studies (BIGS), Tirtayasa Cendekia, Oraganisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, sekaligus Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).