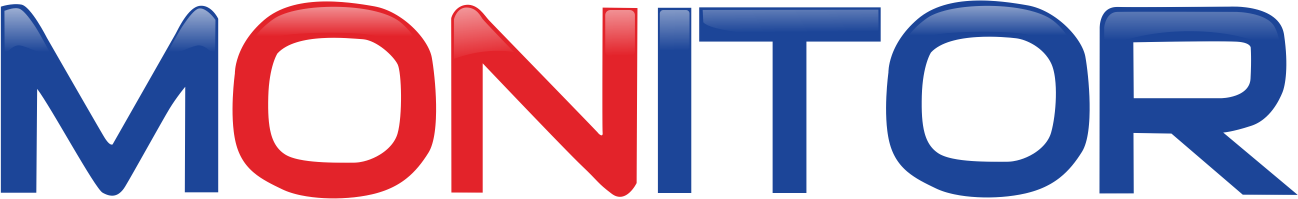Oleh: Imron Wasi*
Wacana reshuffle kabinet muncul kembali dalam jagat politik kontemporer di Indonesia. Hal itu mengemuka sejak Presiden Joko Widodo pertama kali melontarkannya dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. Setelah kemunculan pidatonya pada sidang kabinet tersebut yang telah dipublikasikan, menciptakan diskursus khalayak publik.
Bukan tanpa alasan, mantan Walikota Solo ini melontarkan pernyataan tersebut. Karena, hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah menteri yang kurang optimal di tengah wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kemunculan isu reshuffle bukanlah barang langka dalam panggung politik nasional.
Ia akan hadir, apabila para menteri sebagai agen tidak mampu menerjemahkan misi Presiden, terlebih kinerja yang kurang ideal yang selama ini ditampilkan atau para menteri yang sedikit membelot dari rencana strategis nasional, sesuai program prioritas prinsipal. Meminjam perspektif akademik dari Fukuyama (2005: 63) yang menyatakan, bahwa para agen dalam organisasi sektor negara akan mempunyai agenda-agenda yang sangat berbeda dari agenda-agenda para prinsipal mereka.
Dalam hal ini, penulis mengasosiasikan ‘prinsipal’ sebagai pemegang otoritas tertinggi yang memiliki legitimasi dominan, karena telah dipilih oleh rakyat dalam proses elektoral, yakni Presiden. Sedangkan di satu pihak, penulis menempatkan ‘agen’ berada pada posisi menteri.
Oleh karena itu, masih teringat dalam rasio kita bahwa Presiden pada saat mengumumkan komposisi kabinet menyatakan secara sistematis dan jelas bahwa tidak ada visi atau misi menteri, yang ada hanya visi/atau misi Presiden.
Hubungan antara prinsipal dan agen ternyata sudah sedari awal dilakukan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Selain itu, banyak faktor juga yang dapat memengaruhi terjadinya perombakan kabinet dalam roda pemerintahan, termasuk menteri yang mendapatkan resistensi dari civil society.
Sinyal Perombakan Kabinet
Secara eksplisit Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan terjadinya perombakan kabinet dalam tubuh pemerintahan jilid II. Hal ini terjadi karena di tengah-tengah ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dalam menangani wabah pandemi Covid-19.
Sejumlah menteri menjadi sorotan karena kinerjanya dianggap kurang ideal dan optimal dalam mengaktualisasikan misi Presiden selama ini. Sebagaimana yang telah terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 7-11 Juli lalu.
Sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja menteri, terutama yang menyangkut bidang dalam menangani pandemi Covid-19. Bahkan, lontaran Presiden Joko Widodo perihal reshuffle dikonfirmasi oleh sebagain besar responden (61,4 persen) bahwa perombakan/atau pergantian menteri efektif untuk memperbaiki penanganan Covid-19.
Menilik pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet pada 10 bulan pertama pemerintahannya. Kini, bulan yang sama pada perombakan kabinetnya pada saat itu telah datang, evaluasi kinerja akan menjadi landasan utama pemilik ‘hak prerogatif’.
Dan, secara praksis empiris yang sesuai jajak pendapat Litbang Kompas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (69,6 persen), menilai perombakan kabinet adalah hal yang mendesak dilakukan saat ini. Namun, di tengah dinamika politik global, kita perlu mencermati wacana reshuffle kabinet dari sudut pandang yang berbeda, agar tidak salah mengambil keputusan.
Sebab, perombakan kabinet bukan sekadar simbolik representasi politik semata. Akan tetapi, perombakan kabinet juga perlu memerhatikan hal-hal yang bersifat fundamental bagi perkembangan konsolidasi demokrasi, termasuk hal-hal yang bersifat subtansial.
Message yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada sidang kabinet tersebut, membuat khalayak publik mempunyai asumsi-asumsi dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai analisa kaca matanya. Karena, sudah barang tentu, hanya Presiden yang berhak dan memiliki wewenang untuk memberhentikan, memindahkan, dan mengangkat para menteri atau kita sering menyebutnya sebagai pemilik yang memiliki hak otoritas prerogatif yang tentunya bisa dilakukan dalam rentang waktu tertentu.
Di satu pihak, asumsi lainnya yang berkembang yaitu publikasi sidang kabinet yang didistribusikan kepada khalayak publik cukup jauh setelah sidang kabinet tersebut dilaksanakan. Namun, terlepas dari asumsi-asumsi maupun interpretasi yang berkembang, tentunya message yang disampaikan itu memiliki makna yang secara gamblang juga tampak secara kasat mata atau dengan kata lain ada implikasinya bagi proses reshuffle.
Pertama, lontaran perombakan kabinet ini mewarnai ornamen-ornamen penampilan dalam politik panggung depan (frontstage politics). Tentunya, ini makna pesan yang harus dapat diterjemahkan dengan baik, agar tidak terjadi konsensus politik dagang sapi dalam the secret of garden politics yang tidak bisa ditelaah oleh civil society.
Kedua, secara gamblang ini juga memperlihatkan bahwa Presiden membuka ruang bagi sejumlah partai politik untuk membangun atau memperbaharui kembali Memorandum of Understanding (MoU) yang selama ini telah disepakati sedari awal.
Dalam bahasa lain, membuka kembali proses transaksi politik, karena perombakan kabinet tak bisa dilepaskan dari institusi modern seperti partai politik. Kalau demikian yang terjadi, hal ini bisa menyebabkan Presiden akan tersandera oleh partai politik.
Ketiga, wacana reshuffle ini juga memberikan ketidakpastian, dan sudah barang tentu akan mengganggu psikologis para menteri dan tentunya sejumlah kementerian, misalnya, ekonomi, sosial, tenaga kerja, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketidakpastian ini muncul karena proses reshuffle sudah dibuka ke khalayak publik tanpa tindakan konkret. Dengan kata lain, seolah-olah proses reshuffle ini dalam massa mengambang. Sehingga, akan bermuara pada suatu konsesi atau transaksi politik.
Kalkulasi politik tentunya juga sedang dihitung oleh Presiden. Sebab, apabila terjadi perombakan kabinet, maka akan terjadi dinamika politik dalam koalisi pemerintahan dan akan mengganggu soliditas koalisi. Presiden juga perlu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan sejumlah partai politik, termasuk oposisi.
Apabila dalam waktu dekat terjadi reshuffle kabinet, maka konsekuensinya juga perlu dipertimbangkan secara matang. Karena, meskipun Presiden tidak memiliki beban untuk maju lagi pada periode selanjutnya, tapi roda pemerintahan jilid II ini masih cukup lama.
Dan yang lebih inheren yakni dapat mengganggu agenda-agenda nasional, seperti program-program strategis lainnya yang juga perlu mendapatkan dukungan parlemen, apabila yang dirombak (ganti) itu berasal dari kalangan parpol yang memiliki kursi terbanyak di parlemen, maka ujian di periode kedua Presiden Joko Widodo akan dimulai.
Dalam sistem politik mutakhir, sistem multi-partai dan sistem presidensial tidak akan menjamin kesetiaan para kader parpol terhadap eksekutif. Seperti yang telah didedahkan oleh Scott Mainwaring (1993), bahwa terdapat tiga alasan mengapa kombinasi institusional semacam itu bermasalah.
Pertama, sistem presidensial berbasis multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan eksekutif-legislatif, dan kebuntuan itu berujung pada instabilitas demokrasi. Kedua, sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme.
Ketiga, kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antarpartai dalam demokrasi presidensial, sehingga berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi. Dengan demikian, reshuffle kabinet semestinya memiliki orientasi yang secara spesifik mendukung terhadap perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, bukan malah mengakomodasi sejumlah kepentingan partai politik tertentu yang tentu kesoliditasannya masih diragukan.
Sebab, kecenderungan ke arah politik pemburu rente (rent-seeking) dan oportunisme politik (pork-barrel politics) terjadi karena sejumlah keadaan, seperti distrik-distrik elektoral banyak anggota, jumlah pemilih yang secara geografis kecil, dan perwakilan proporsional terbuka, meskipun melekatnya patronase dalam sistem kepartaian sangat bergantung pada rangkaian historis perluasan hak suara dan reformasi birokratis (Shefter, 1993).
Dalam upaya mendukung perkembangan konsolidasi demokrasi juga dapat pula dengan memerhatikan asas meritokrasi, akseptabilitas, profesionalitas, dan peningkatan kemampuan (capacity building) dalam agenda wacana reshuffle.
Menentukan Menteri dalam Kabinet
Seperti yang telah diulas oleh penulis, bahwa untuk melakukan perombakan kabinet diperlukan upaya-upaya yang secara gamblang dapat memperkokoh konsolidasi demokrasi, terutama mengkonstruksi koalisi secara solid; asas-asas yang juga perlu ditingkatkan yakni peningkatan kemampuan (capacity building), meritokrasi, akseptabilitas, dan profesionalitas.
Dan, yang paling esensial juga yaitu mendengar aspirasi khalayak publik. Dalam reshuffle mendatang, rakyat memiliki asa akan sebuah sosok pemimpin transformasional (menteri) yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, terutama yang dapat mengatasi problematika kebangsaan. Salah satunya yang sedang dihadapi oleh negara-negara transnasional, termasuk Indonesia, yaitu wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Di masa pemerintahan jilid II, mantan Walikota Solo ini juga diharapkan mampu membuat komposisi kabinet lebih profesional, agar dapat membantu kinerja Presiden. Dalam membentuk komposisi zaken kabinet (mengganti dan memindahkan), Presiden perlu memerhatikan track record, kompetensi di bidang yang akan digeluti, keilmuan, dan pengalamannya mumpuni.
Dan salah satu prinsip yang perlu dicermati yakni the right person in the right place. Sebelum hendak melakukan reshuffle, pasti ada institusi yang mengukur parameter tingkat kinerja para menteri dalam sebuah kabinet. Tak sampai berhenti di situ, pasti pimpinan parpol (koalisi) sebagian ada yang diajak berbicara. Karena, keterwakilan politik pasti juga akan dipertimbangkan secara matang. Sebab, partai politik mempunyai kekuatan yang super dominan di Indonesia.
Biasanya, di tengah sistem presidensialisme dan sistem multi-partai, realitas politik juga akan lebih rumit dan sukar. Karena, banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi. Sementara itu, untuk membentuk kabinet ahli tak semudah mengedipkan mata.
Sebab, sistem presidensial yang masih dijalani tampak masih setengah hati. Artinya, eksekutif tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan mulus, tanpa keterlibatan parlemen di dalamnya. Jadi, sudah dapat dipastikan, selama sistem multi-partai dan sistem presidensialisme dilakukan secara bersamaan, maka siapa pun pemerintahannya, akan mengakomodasi kepentingan partai politik. Sebab, di lembaga parlemen terdapat para kader partai politik.
Selanjutnya, yang juga perlu diperhatikan yaitu langkah Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet. Pada periode awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo juga cukup sering melakukan reshuffle, termasuk mereposisi sejumlah menteri.
Pada saat yang sama, juga mengakomodasi sejumlah partai politik yang datang terakhir. Pada periode awal, memang dibutuhkan parpol yang memiliki keterwakilan politik di parlemen cukup dominan untuk menjaga keseimbangan politik.
Dengan kata lain, ada keterkaitan relasi kuasa yang digunakan. Namun, di periode kedua, Presiden Joko Widodo yang didukung oleh sejumlah parpol besar tampaknya tak perlu dukungan dari parpol oposisi lainnya. Oleh karena itu, peta politik nasional akan berubah apabila terjadi perombakan kabinet.
Secara faktual, sikap kehati-hatian juga menjadi salah satu pertimbangan utama belum dilakukannya reshuffle. Pidato dalam sidang kabinet paripurna yang lalu, hanya suatu bentuk pesan yang harus segera dianalisa oleh partai politik dengan mempersepsikan sesuai analisa tim parpol.
Sebab, gelembung isu dan gelembung politik seputar rencara reshuffle biasanya dipicu oleh tiga faktor, yaitu: pernyataan presiden sendiri yang ditangkap sebagian kalangan mengindikasikan kekecewaan atas capaian kinerja satu atau beberapa pos kementerian; isu perombakan ramai setiap mendekati bulan-bulan evaluasi tahunan kinerja menteri dan kementerian; dan faktor pemantiknya adalah soal relasi kuasa (Gun Gun Heryanto, 2019:254-256).
Berdasarkan perspektif di atas, penulis melihat dari sudut pandang yang sedikit sama yaitu pada sidang kabinet paripurna yang memicu keriuhan khalayak publik itu juga tampak sesuai dengan perspektif studi yang telah dilakukan oleh Heryanto (2019), bahwa secara faktual, tampaknya Presiden kecewa terhadap kinerja para menteri.
Selain itu, momentum evaluasi kinerja para menteri yang telah dilakukan oleh lembaga atau unit tertentu di dalam lingkungan istana pemerintahan juga bisa menjadi parameter atau pertimbangan utama Presiden dalam melakukan reshuffle kabinet; sekaligus momentum yang tepat, untuk melakukan kajian lebih komprehensif ihwal kinerja para menteri di tengah wabah pandemi.
Di satu pihak, pidato pada sidang kabinet paripurna itu juga mengandaikan bahwa Presiden juga berhak melakukan peningkatan kepercayaan (trust) rakyat melalui sidang kabinet dan didistribusikan ke khalayak publik untuk mengundang reaksi khalayak publik, yang tentunya akan bermuara pada legitimasi rakyat terhadap pemerintah, dalam hal ini Presiden.
Di lain pihak, pidato yang disampaikan juga karena sudah masuk dalam laporan evaluasi kinerja para menteri. Sehingga, semestinya ini menjadi bahan diskursus internal kabinet. Dan, hal ini adalah langkah politik untuk menciptakan image politik yang baik.
*Penulis merupakan Peneliti di Banten Institute for Governance Studies, BIGS