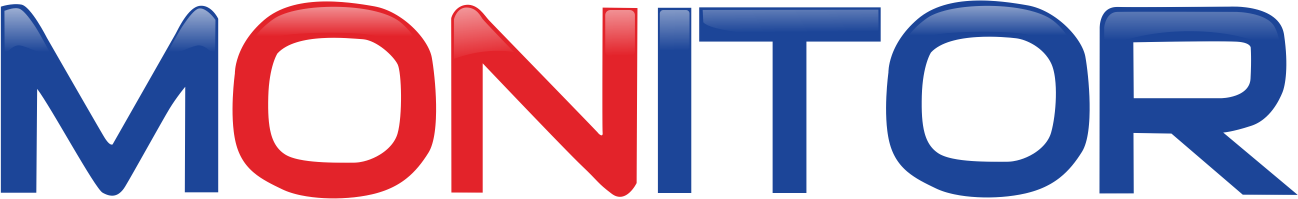Boy Anugerah *
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia pertama kali dihelat pada Juli 2005 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, kepala daerah dipilih secara representatif oleh parlemen daerah. Perubahan ini secara total telah merubah wajah demokrasi di tingkat lokal.
Jika pada era sebelumnya rakyat hanya bisa menjadi penonton dan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan pada wakil-wakil yang duduk di parlemen, mekanisme langsung menempatkan mereka sebagai direct voters yang mempunyai kuasa penuh untuk memilih para kandidat dalam Pilkada.
Sejatinya mekanisme Pilkada dimaksudkan guna mewujudkan kesejahteraan daerah. Rakyat di daerah diberikan kewenangan untuk memilih para wakilnya yang dianggap memiliki kompetensi dan komitmen dalam merealisasikan aspirasi mereka.
Dengan memilih secara langsung, maka kepala daerah terpilih akan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional kepada rakyat yang memilih. Pilkada juga bukan sekedar pesta demokrasi belaka, tapi juga sebagai media perantara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah di segala bidang.
Permasalahan Pokok
Namun demikian, seperti halnya dalam praksis politik pada jamaknya, selalu ada jurang antara das sollen dan das sein, antara ekspektasi dan realita. Alih-alih menciptakan narasi besar tentang kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah, dalam dua dekade terakhir sering kita jumpai para kepala daerah terpilih duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa korupsi dengan berbagai modus, mulai dari suap perizinan konsesi di sektor sumber daya alam, hingga kolusi dalam hal pemilihan birokrat di pemerintahan daerah. Merujuk data ICW, dalam kurun 2004-2018, sedikitnya 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan ditangani oleh KPK.
Ada banyak permasalahan lainnya yang sifatnya krusial yang membutuhkan tidak sekedar atensi dari para pemangku kepentingan politik tanah air, tapi strategi jangka panjang dalam membenahi kualitas demokrasi. Narasi Pilkada langsung menjadi tawar tatkala kewenangan untuk mencalonkan kandidat dalam kandidasi berada di tangan partai politik dan gabungan partai politik.
Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa situasi dan kondisi partai politik saat ini disesaki dengan kekuatan oligarki, yang mana keputusan elit partai politik menjadi determinan utama. Sebagai konsekuensinya, kerapkali kandidat yang diusung dalam Pilkada adalah kandidat pilihan elit politik dengan karakteristik padat modal, namun minim kompetensi dan integritas.
Pilihan elit politik sebagian besar bermain di dua kategori calon, yakni pengusaha yang hendak terjun ke dunia politik, atau calon yang berasal dari figur publik seperti artis, penyanyi, dan pengawak dunia hiburan lainnya yang memiliki popularitas di masyarakat. Tak semuanya tentu, tapi sebagian besar dari calon-calon tersebut kerapkali tidak cukup kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah, sehingga terjadi penambahan bobot beban pekerjaan terhadap pejabat struktural di bawahnya. Dengan kondisi sedemikian, sulit diharapkan terbentuk model kepala daerah yang mampu menghembuskan narasi besar dan menjadi gerbong perubahan.
Resesi demokrasi dalam konteks Pilkada kian menguat ketika muncul fenomena calon tunggal, yakni satu pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik. Memang kondisi ini tak serta-merta menjadikan calon tunggal tersebut keluar sebagai pemenang, karena harus diadu terlebih dahulu dengan bumbung kosong. Akan tetapi rakyat menjadi tidak punya banyak pilihan karena ‘dipaksa’ oleh gabungan partai politik untuk memilih calon yang disodorkan.
Kondisi ini mengalami kecenderungan semakin meningkat. Jika pada Pilkada 2015 jumlah calon tunggal hanya tiga pasangan saja, pada 2017 meningkat menjadi sembilan pasang calon. Pada 2018, jumlah calon tunggal meledak hingga menembus angka enam belas pasang calon. Trend kenaikan ini diprediksi akan kembali terjadi pada Pilkada 2020 nanti.
Fenomena calon tunggal ini sangat tidak sehat bagi cita-cita mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di daerah. Di satu sisi, hal ini terjadi karena adanya dominasi partai politik tertentu di daerah. Dominasi ini koinsiden dengan kepentingan partai-partai politik minor yang lebih memilih masuk ke lingkaran kekuasaan, ketimbang bersusah payah menjadi oposisi.
Di sisi lainnya, celah lebar pelemahan demokrasi ini terjadi karena kelemahan yang sifatnya regulatif. Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada tidak mengatur batas maksimal kekuatan partai yang dapat mengusung calon di Pilkada. Pada Pasal 40 hanya disebutkan perihal syarat minimal yakni penguasaan akan 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen jumlah perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Angin Perubahan
Beragam belenggu di sekitar penyelenggaraan Pilkada dalam beberapa tahun terakhir pada dasarnya bukan tanpa jalan keluar. Permasalahannya hanya terletak pada kemauan politik (political will) dari para elit partai politik serta para pemangku kepentingan pemerintahan tanah air.
Solusi juga tak sulit diimplementasikan apabila kalangan pers dan masyarakat madani lainnya siap berkhidmat dalam menuntaskan cita-cita reformasi, berpihak pada rakyat, dan tidak menjadi bagian dari politik kekuasaan.
Bisa dibayangkan bagaimana kelamnya politik kekuasaan yang menautkan antara oligarki elit politik dengan kalangan pers dan masyarakat madani yang juga berburu kekuasaan. Nasib demokrasi berada di tubir jurang kehancuran.
Perubahan pertama yang bisa diusung adalah dengan melakukan reformasi sistem rekrutmen partai politik, baik rekrutmen untuk menjaring anggota atau kader, maupun rekrutmen untuk menjaring calon kepala daerah.
Studi yang diselenggarakan oleh KPK dan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merekomendasikan penerapan sepuluh prinsip yang harus dipatuhi dalam rekrutmen partai politik, yakni prinsip loyalitas, bersih, keterbukaan, akuntabilitas, meritokrasi, demokratis, desentralisasi, kecukupan pembiayaan (self-sufficiency), humanis, dan non-partisan.
Agar bersifat operasional, kesepuluh prinsip tersebut harus dituangkan ke dalam teknis rekrutmen, dipatuhi oleh segenap pihak yang terlibat, dimonitoring, serta dievaluasi dengan baik pelaksanaannya.
Dalam konteks revitalisasi sistem rekrutmen, juga sempat muncul kontestasi pemikiran mengenai mana yang lebih signifikan antara model partai politik massa atau partai politik kader. Menurut hemat penulis, hal tersebut sifatnya situasional.
Untuk partai politik yang baru berdiri, yang mana pemenuhan syarat struktural dan keanggotaan sangat dipertimbangkan sebagai basis hukum pendirian, maka model partai massa tak haram untuk dilakukan. Namun demikian, pasca pendirian, minimal setahun pasca pendirian, sistem kaderisasi harus dimaksimalkan. Hal ini berbeda dengan partai politik yang sudah mapan, yang mana basis rekrutmen sudah seharusnya konsisten pada prinsip kaderisasi.
Linkage antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik akan semakin kuat dan berkorelasi dengan kinerja positif para kader yang duduk di alat-alat negara nantinya.
Perubahan kedua adalah perubahan yang sifatnya regulatif. Fenomena calon tunggal telah mengoyak-ngoyak sendi demokrasi, serta melemahkan hak-hak sipil dan politik warga negara. Kandidasi dimonopoli oleh mereka yang bercuan dan sanggup membayar partai politik saja. Oleh karenanya dibutuhkan perubahan terhadap regulasi yang mengatur Pilkada.
Perlu dibuat model batasan terhadap gabungan partai politik yang mengusung, sehingga tidak semua partai politik di daerah terbuhul dalam satu simpul, semata-mata agar terakomodasi di bilik kekuasaan. Akan lebih baik apabila juga dimasukkan skema uji publik untuk calon yang diusung.
Terakhir, adalah penguatan kontribusi gerakan masyarakat sipil yang konsisten menguatkan pendidikan politik masyarakat. Tak dimungkiri saat ini terjadi kemunduran dalam gerakan masyarakat sipil, khususnya yang berjuang di jalur demokrasi.
Persoalan logistik (baca: dukungan dari donor) dan kurangnya daya tarik gerakan masyarakat sipil di mata publik menjadi kendala utama. Namun demikian, kondisi ini seyogianya menjadi silver lining bagi gerakan masyarakat sipil untuk mewujudkan kemandirian organisasi, tidak bergantung pada support system dari donor asing. Sehingga gerakan yang dilakukan benar-benar bersih, patriotik, dan membawa arah positif bagi penguatan demokrasi tanah air.
Gelaran Pilkada 2020 masih menyisakan lima bulan lagi. Badai Corona yang menghantam Indonesia dalam satu bulan terakhir ini berpotensi besar menyebabkan pemunduran jadwal pelaksanaan Pilkada. Kondisi ini bisa dimaksimalkan oleh segenap pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi perbaikan dalam menopang penyelenggaran Pilkada yang lebih bermutu dan bermartabat.
Partai politik masih punya banyak waktu untuk menyiapkan calon yang berintegritas dan kredibel. Para penyelenggara Pilkada juga masih punya waktu untuk memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan demokrasi berbasis kesejahteraan bagi rakyat. Menarik dicermati!
*) Penulis merupakan Mahasiswa Studi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik di SGPP Indonesia. Tulisan merupakan pendapat pribadi