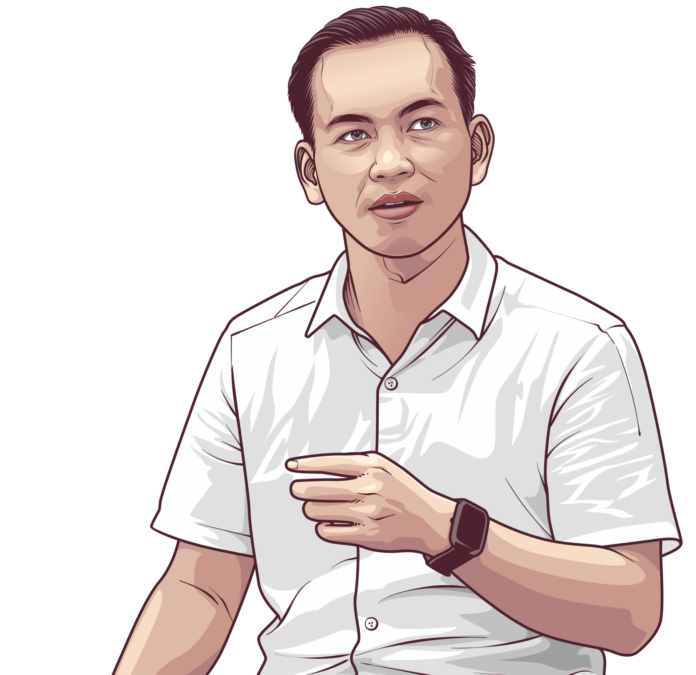Oleh Dadangsah Manjalib*
“Homo Homini Lupus” sebuah peribahasa Romawi Kuno yang kemudian dipopulerkan oleh Thomas Hobbes (abad ke-17) terutama dalam karyanya De Cive (warga negara). Homo Homini Lupus merupakan bahasa latin yang bermakna “Manusia Adalah Serigala Bagi Manusia Lainnya”. Konsep ini digunakan oleh Thomas Hobbes untuk menjelaskan kondisi alamiah manusia sebelum adanya negara, di mana manusia saling memangsa dalam kondisi tanpa hukum, tanpa adanya negara.
Namun, setelah kita bernegara dengan penataan hukum dan kekuasaan, apakah kita sudah berhenti memangsa antar sesama? Atau malah pemangsaan semakin tidak berimbang dengan selubung hukum dan kekuasaan. Dan tentu saja, akar dari tabiat saling mangsa ini yakni perebutan dan penguasaan sumber daya.
Keserakahan manusia inilah memicu kerusakan, tidak hanya mengancam eksistensi sesamanya, namun juga mengancam eksistensi semesta. Padahal, jika saja manusia bahu-membahu dan tidak bertindak serakah, niscaya akan membawa pada kemakmuran yang berkeadilan dan keselamatan pada semesta. Sebagaimana yang dituturkan oleh Mahatma Gandhi pada forum Round Table Conference 1931 di London “Bumi tuhan memberikan cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk keserakahan seseorang”.
Untuk itu kiranya penting bagi kita melakukan tata kelola serta kebijakan pembangunan dengan berpegang pada prinsip sustainability. Apa itu Sustainability? Yaitu suatu prinsip moral dalam upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan kelestarian jangka panjang, dengan menyeimbangkan tiga pilar utama: lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Hakikat Sustaibanility
Sebelum revolusi industri, sistem ekonomi dan ketenagakerjaan belum begitu kompleks. Pada tahap ini, prinsip-prinsip keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan berkembang secara intuitif, hal ini tidak lain adanya faktor sosial etik yang terus berkembang di tengah masyarakat. Hanya saja, kesadaran etik demikian, ketika itu belum terbangung atau dianut secara struktural pemerintah atau dalam budaya dan regulasi pada suatu entitas bisnis hubungan industrial.
Memang, revolusi industri yang ditandai dengan penemuan energi tenaga uap oleh James Watt pada tahun 1763 telah memantik transformasi dan menjadi tonggak sejarah peradaban manusia. Namun revolusi industri memiliki catatan hitam, yang mana eksploitasi dan produksi secara masif tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya berujung pada ketimpangan dan krisis sistemik.
Hal inilah kemudian muncul perlawanan sosial yang diantaranya ditandai terbitnya Das Kapital edisi pertama karya Karl Marx tahun 1876, yang mana, di antara pokok pikirannya Marx meyakini, jika pemodal hanya berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan aspek keadilan sosial atau kesejahteraan kaum buruh, maka akan tercipta ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, sistem kapitalis adalah bom waktu. Upah yang rendah menjadikan daya beli masyarakat, lemah. Sementara produksi barang kian meningkat, pada puncaknya ekonomi akan collapse akibat over produksi yang tidak diimbangi dengan daya beli. Pabrik membanjiri pasar namun rakyat tidak mampu membeli.
Kemudian pada tahun 1930 terjadi peristiwa krisis global yang dikenal dengan Great Depression. Peristiwa ini mengkonfirmasi relevansi pandangan Marx, yang mana melalui hasil analisis ekonom inggris, John Maynard Keynes mengungkapkan, pemicu krisis ekonomi global kala itu akibat turunnya daya beli masyarakat berimplikasi pada perlambatan laju produksi dan pemutusah hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Situasi demikian menyebabkan kredit macet membengkak dan runtuhnya saham wall street.
Setelah itu, mulai muncul kajian dan narasi yang mengarahkan pada kesadaran kolektif atas konsekuensi dari ketidak selarasan pembangunan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Seorang ekonom Amerika, Howard R. Bowen menyerukan akan pentingnya untuk melihat value ekonomi dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya sekedar dari pertumbuhan dan keuntungan semata, melainkan juga mencakup distribusi kesejahteraan sosial dan keamanan nasional. Yang mana dalam bukunya ‘Social Responsibility of the Businessman’ Howard menggunakan peristiwa Great Depressionsebagai contoh historis untuk mendukung gagasannya dalam mendorong kesadaran tanggungjawab sosial yang terbangun secara struktural dalam hubungan industrial.
Selain itu, berbagai temuan dari pegiat lingkungan sebagaimana buku “Silent Spring” yang ditulis Rachel Carson (1962) mengenai dampak penggunaan pestisida dan Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) “Our Common Future” 1987 yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland (PM Norwegia) dan disertai Emil Salim sebagai tokoh mewakili Asia Tenggara saat itu.
Rentetan dari peristiwa dan perkembangan sosial yang terjadi, mengkonstruksi secara historis akan gagasan sustainability. Bahwa untuk mencapai stabilitas, keamanan dan kemakmuran secara global, perlu untuk berpegang pada prinsip moral yang dinamakan sustainability, yaitu prinsip keadilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang bukan hanya untuk generasi pada saat ini, namun juga keadilan pada generasi mendatang, yang mana prinsip ini bertumpu pada keselarasan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi atau kesejahteraan.
Selanjutnya prisip ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak 2007 melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan corporate social responsibility (CSR), diantaranya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Peraturan No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, hingga peraturan turunan berupa Permen dan Perda. Lalu baru kemudian prinsip sustainability diadopsi secara global oleh PBB melalui KTT di New York 2015 dengan apa yang dikenal sebagai program sustainable development goals (SDGs).
Relevansi Konstitusi
Berdasarkan epistemologi sustainability yang telah diuraikan, tentu kami mengajak pemangku kebijakan untuk melihat sustainability bukan hanya sebatas implementasi sempit yang dituangkan hanya dalam ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi korporasi, namun prinsip sustainability ini hendaknya menjadi acuan moral dari setiap kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Doktrin sustainability bukanlah sesuatu hal yang asing untuk kita pahami, melainkan ia merupakan satu warna dari buah pikir founding father kita dalam merumuskan konstitusi negara ini. Sebagaimana pembukaan UUD 1945 alinea ke II dan ke IV yang menegaskan frasa adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia (tak terkecuali pada generasi mendatang) sebagai cita-cita luhur bangsa dan tujuan bernegara.
Karena itu, sudah seharusnya pemangku kebijakan ataupun stakeholders yang terlibat dalam pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam untuk bertindak bijak berpegang teguh pada asas keadilan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial demi mencapai cita-cita luhur bangsa dan tujuan negara yakni adil makmur untuk seluruh rakyat indonesia.
Jika prinsip moral ini diabaikan, maka akan terjadi disparitas, kesenjangan, dan disintegrasi yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, sustainability merupakan jalan untuk pemenuhan keadilan, kemakmuran dan keamanan sebagai perekat keutuhan bangsa Indonesia yang merdeka untuk selama-lamanya.
*Penulis merupakan Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Nasional (UNAS) yang juga Penggerak Sustainability