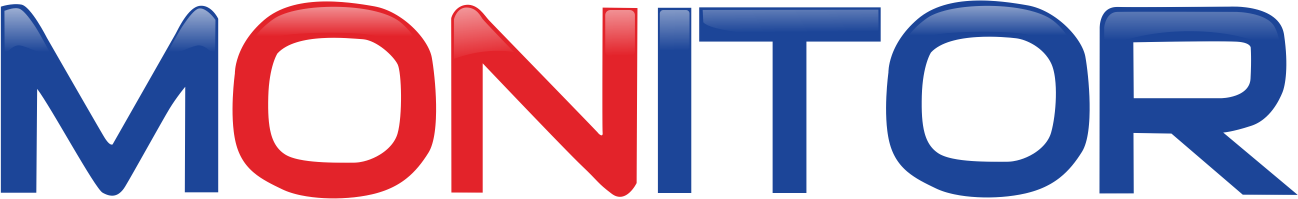Oleh: Hasin Abdullah*
Pasca Richard Eliezer memutuskan diri untuk menjadi justice collaborator telah mendapat apresiasi dari publik termasuk dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan, kesiapan Bharada E menjadi saksi pelaku peristiwa pidana tersebut telah menunjukkan kepatuhannya hukum di Indonesia untuk membongkar fakta hukum seterang-terangnya terkait konspirasi dan pembunuhan berencana Birgadir J pada persidangan di PN
Jakarta Selatan.
Sebagai seorang saksi pelaku (justice collaborator) yang siap berkata jujur di persidangan. Alhasil, ia tak sia-sia dalam membuktikan kasus pembunuhan ini bahwa Ferdy Sambo sebagai aktor intelektual utama atas terjadinya pembunuhan berencana. Tapi, pertanyaannya ini perlu diajukan pada Jaksa Penuntut Umum, kenapa seorang justice collaborator yang berperan dan berjasa besar mendapat tuntutan berat yaitu 12 tahun penjara sebagaimana ia dianggap secara sah dan meyakinkan bahwa Richard Eliezer melakukan tindakan pidana sesuai pasal 340 subsider pasal 338 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ancaman pidana 12 tahun penjara yang langsung dibacakan oleh JPU seolah-olah tidak didasarkan pada pembuktian saksi pelaku yaitu Bharada E. Di mana dalam sistem peradilan pidana, setiap legal standing JPU bukan hanya merujuk pada fakta-fakta persidangan, melainkan juga pada saksi pelaku yang kian berani menyampaikan keterangannya dengan jujur, dan koperatif. Dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP substansinya cukup jelas bahwa keterangan saksi dapat menjadi alat bukti tentang benar tidaknya suatu peristiwa pidana. Hal itu juga termuat dalam asas hukum yang berbunyi “unus testis nullus testis” di mana setiap keterangan saksi termasuk pelaku yang bekerjasama dapat menjadi alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana.
Kepatuhan dan kesadaran hukum Richard Eliezer dalam kasus ini patut meyakinkan JPU untuk kembali menimbang dakwaan yang terlanjur dibacakan di persidangan. Pasalnya, ia telah bersikap gentle siap membuka secara transparan, sehingga pidato pembelaan atau pledoi yang dikenal dalam istilah hukum pidana adalah pertimbangan bagi majelis hakim
apakah tuntutan JPU bisa gugur atau tidak sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku.
Justice Collaborator Vs JPU
Richar Eliezer sebagai seorang justice collaborator dalam sidang pledoi mengangkat judul “Apakah Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara”. Judul ini asal usulnya adalah mengingatkan JPU, dan majelis hakim agar kembali menimbang ulang terkait perannya sebagai saksi pelaku yang berkata benar, dan jujur sehingga harus mendapat perlakuan khusus seperti perlindungan, dan keadilan bagi setiap pelaku yang bekerjasama.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu pada hakikatnya sebagai penegasan terhadap jenis kelamin penegakan hukum, sehingga tuntutan JPU memang proporsional, dan rasional.
Dalam kaintan penegakan hukum pidana, legal reasoning JPU kurang memenuhi substansi hukum yang berlaku. Pasalnya, dakwaan yang jelas-jelas mengaburkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 dan rekomendasi LPSK menjadi preseden buruk terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia. Jadi, hukum bukan hanya
sekumpulan peraturan perundangan-perundangan, namun di sisi lain hukum mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang ujung tombaknya adalah keadilan.
Kini proses hukum yang selama ini ditempuh mulai dari awal persidangan yaitu pembuktian, saksi, dakwaan, dan replik, hingga pada tahap sidang duplik. Penuntut Umum kian terlanjur mendakwa dengan caman pidana 12 tahun penjara. Pada hemat penulis, dakwaan tersebut seakan-akan tidak ada pasal yang dapat diterapkan dalam tuntutan,
sehingga secara substantif alasan apapun tidak dapat diterima akal sehat publik.
Pun dugaan perselingkuhan juga termaktub dalam dakwaan tapi hal itu tak mampu dibuktikan secara hukum pidana materil. Artinya, ketika dalam pembuktian tersebut dangkal, maka dakwaan bagi Bharada E dalam konteks sistem peradilan pidana tak dapat meyakinkan hakim secara substantif dan sempurna. Bagaimana mungkin dalam situasi penegakan hukum terhadap oknum polisi hanya didasarkan pada bukti permulaan
yang tak cukup?
Pertanyaan di atas sangat relevan jika dikorelasikan dengan kronologi yang terjadi dan kaitannya dengan keterangan para terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, keterangan objektum litis seorang justice collaborator setidaknya dapat membuktikan unsur kejahatan para terdakwa lain khususnya Ferdy Sambo, dan Putri Candrawati. Konspirasi kasus
polisi tembak polisi inilah menjadi pelajaran bagi setiap institusi penegak hukum kedepannya.
Tantangan Majelis Hakim
Kasus pembunuhan Brigadir J ini hampir sampai pada tahap putusan oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan. Publik pasti tahu psikologis hakim sebagai pemutus perkara, sehingga setiap alat bukti, keterangan saksi, dan pledoi setiap terdakwa adalah tantangan serius bagi majelis hakim untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Hakim dalam sistem peradilan pidana ini dapat memutus perkara berdasarkan asas in dubio prorio (keyakinan/sense) dengan menilai, dan menimbang-nimbang hukum secara filososis, yaitu unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini yang harus menjadi terobosan bagi majelis hakim di persidangan supaya tidak memutus atas dasar pengaruh
framing media massa, sebab pemberitaan punya potensi merusak keyakinan hakim.
Menurut hemat penulis, tantangan majelis hakim terdapat beberapa hal yang harus direkonstruksi. Pertama, soal rekam jejak majelis hakim dalam hal kapasitas yang pasti tak diragukan lagi. Kedua, independensi majelis hakim dalam menghasilkan putusan yang kredibel, dan objektif. Ketiga, soal integritas dan akuntabilitas yang menjadi pelengkap dalam memutus perkara ini, sehingga pun harus bersikap tegas, dan tak boleh pandang bulu.
Keempat, hakim harus proporsional dalam menciptakan putusan tersebut, sebab hal ini tidak hanya integritas aparatur pengadilan yang dibutuhkan, melainkan terkait integritas saksi pelaku yang kian berani berkata jujur, dan siap menerima konsekuensi hukumnya. Catatan inilah paling tidak majelis hakim merekonstruksi ulang supaya hukum, dan keadilan tak terpisahkan.
Hukum untuk Richard Eliezer
Kewenangan dalam mengeksekusi putusan sepenuhnya adalah otoritas majelis hakim, penyidik hanya menggelar hasil penyidikan, sedangkan penuntut umum adalah menentukan pasal-pasal yang terkait dalam dakwaan. Oleh sebab itu, jalan tengah yang harus ditempuh dalam persidangan oleh majelis hakim ialah merekonstruksi hukum, dan
keadilan.
Di sinilah amanah majelis hakim adalah mengupayakan kepentingan hukum yang adil sebagaimana teori hukum progresif Sajipto Rahardjo yaitu mengenyampingkan hukum yang tidak adil yang tujuannya ialah hukum untuk masyarakat. Tetapi, bukan masyarakat untuk hukum. Pendekatan ini relatif mampu meyakinkan majelis hakim dalam menerapkan putusan.
Harapannya pada majelis hakim agar dapat memutus kasus seadil-adilnya, dan didasarkan pada hukum nurani yang dapat diterima logika masyarakat. Pembuktian yang diperoleh melalui persidangan sampai menjelang akhir harus membentuk keyakinan hakim bahwa tanpa kejujuran, dan keberanian justice collaborator kasus ini tidak akan terang benderang.
Keadilan sebagai jalan tengah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Keduanya tentu menjadi pelengkap bahwa hukum memandang dimensi perlindungan di sisi lain keadilan harus mendekati perasaan yaitu nuarni. Maka, setiap putusan di dalamnya terdapat keadilan yang dapat melakukan anolir terhadap hukum-hukum yang tidak adil.
Pada dasarnya, hukum tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, tetapi eksekutor keadilan bergantung pada pertimbangan majelis hakim sejauh mana ia memakai metode tafsir rechtsvinding yang hal ini mendorong hukum supaya tegak sesuai pada tempatnya. Apalagi Richard Eliezer selain menjadi saksi pelaku juga mengakui kesalahannya di sisi lain.
*Penulis merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesian Legal Studies (CELES)