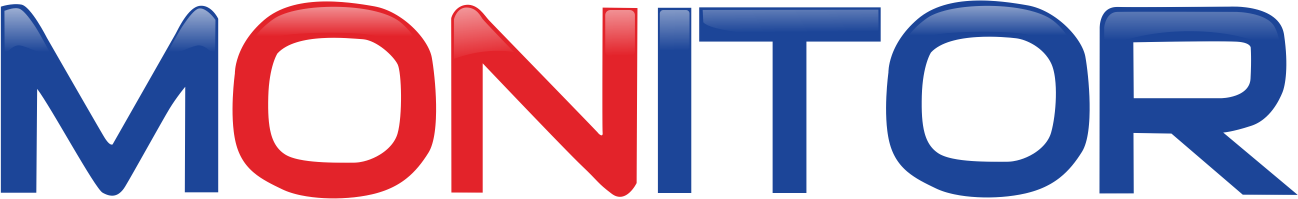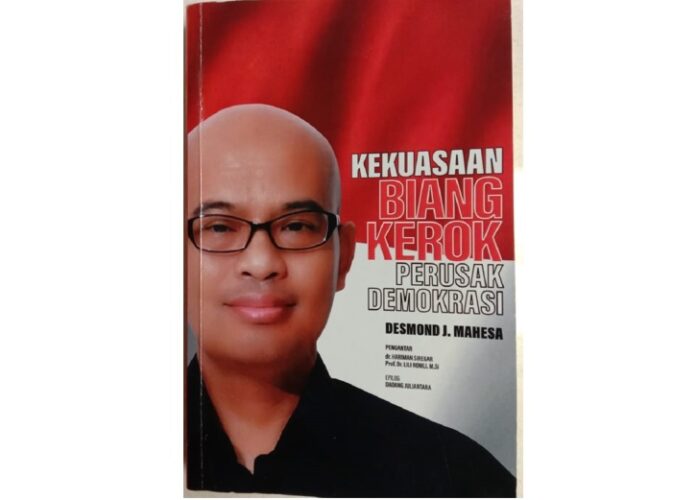Oleh: Rahmat Kamaruddin (Gerakan Milenial Indonesia)
[Review buku “Kekuasaan Biang Kerok Perusak Demokrasi” karya Desmond J. Mahesa]
Alkisah, Raja Namrud murka. Ia pun membawa Ibrahim ke perapian. Membakarnya hidup-hidup. Seekor burung pipit tampak mondar-mandir ke sungai. Dengan paruhnya yang mungil, ia mengambil air, berupaya memadamkan kobaran besar api.
Ikhtiar si burung kecil tentu tak akan mampu membuahkan hasil yang diharapkan. Beberapa hewan lain keheranan. Seraya menyangsikan perjuangan si burung kecil, mereka bertanya, “Mengapa kamu bersusah payah mengambil air, sedangkan kamu tahu api besar yang membakar Nabi Ibrahim tidak akan hilang dengan sedikit air yang kamu siramkan itu?”
Si burung kecil menjawab, “Walaupun aku tahu aku tidak akan mampu memadamkan api tersebut, namun aku telah berusaha menegakkan kebenaran dengan segenap kemampuanku. Aku telah menentukan di mana aku berpihak, menempatkan loyalitas dan pembelaanku.”
Kisah di atas disadur dari halaman 309 buku karya Desmond J. Mahesa (selanjutnya DJM) berjudul “Kekuasaan Biang Kerok Perusak Demokrasi”. Ada semacam rasa gundah yang tak terperikan membebani batin DJM sebagai Wakil Rakyat karena belum dapat berbuat banyak menyaksikan betapa pilunya nasib demokrasi Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini.
Menurutnya, kekuasaan belum berpihak pada kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Aroma kuat perselingkuhan cinta segitiga antara eksekutif, legislatif dan yudikatif melahirkan rangkaian skandal penegakan hukum di republik ini. Konsolidasi elite nyaris tak menyisakan ruang lagi untuk bersuara. Rakyat pun seolah-olah tidak lagi punya wakil di Senayan.
“Lemahnya kekuatan partai politik di Senayan memang telah membuat Pemerintahan berjalan melenggang tanpa adanya rintangan yang menghalanginya. Dengan segala dukungan yang ada, tidak mengherankan jika keberadaan Presiden Jokowi tidak tergoyahkan posisinya. Setiap narasi yang menyudutkan presiden bisa langsung dilibas tanpa merisaukan dampak yang ditimbulkannya. Pada akhirnya, muncul dugaan yang menyebut pemerintahan sekarang mirip gaya Orba dengan tampilan berbeda. Apakah Pemerintah saat ini memang sudah mewarisi gaya Orba yang telah berhasil ditumbangkan oleh para mahasiswa?”, tulis DJM (h.308).
Menyemai otokritik
Buku ini merupakan kelanjutan dari karya DJM sebelumnya, “Prahara Demokrasi di Tengah Pandemi”. Terbit pada penghujung 2020 lalu. Pada 2021 kali ini, DJM kembali melanjutkan upayanya menyemai kritik, selain kepada Pemerintah dan penegak hukum, terutama kepada lembaga legislatif tempat di mana kini ia tengah berjuang merawat demokrasi. Sebuah otokritik bagi DPR yang menurutnya kini seperti sedang mati suri.
Kompilasi tulisan DJM pada buku ini dibagi menjadi enam. Masing-masing dengan judul: “Kekuasaan yang Merusak dan Imbasnya pada Kelembagaan Negara”, “Ironi Kekuasaan dan Pentingnya Kontrol Kekuasaaan”, “Belantara Masalah di tengah Pandemi Virus Corona”, “Cita-Cita Reformasi Tinggal Catatan dan DPR yang Mati Suri”, “Sekaratnya KPK di Tangan Penguasa”, dan “Wajah Suram Aparat Kepolisian”.
Dua prolog dari dua tokoh pada latar belakangnya masing-masing amat berarti bagi karya DJM, terutama terkait posisi DJM sebagai aktivis ‘98 yang kini menjabat sebagai wakil rakyat di Senayan. Adalah Hariman Siregar, tokoh senior pergerakan dan mantan aktivis Malari, memberikan kesaksian kebesaran hati DJM perihal kasus penculikan dirinya.
Bagi DJM, tidak ada urusan pribadi jika kepentingan bangsa dan negara memanggil. Memaafkan adalah jalan untuk kita menuju masa depan. Hal ini tentu saja meruntuhkan pandangan beberapa pihak yang keliru memahami DJM. Hariman menulis,
“Di tengah isu Prabowo Subianto terlibat penculikan dirinya, di kemudian hari ia justeru menjadi kader mantan Danjen Kopassus tersebut. Itulah hebatnya Desmond, ia pribadi pemaaf. Di kepalanya saat itu: siapapun yang mengajak berjuang memperkuat nasionalisme maka ia akan menyambutnya. Jadi bukan karena sindrom stockholm (tawanan yang jatuh cinta pada penculiknya),” (h.xxvi).
Tilikan akademik oleh Prof. Dr. Lili Romli, M.Si pada prolognya, mewartakan kepada kita demokrasi dengan berbagai keunggulannya. Apa saja gerangan keunggulan demokrasi sehingga ia patut kita rawat? Meminjam Robert A. Dahl, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI itu menulis,
“…ada sepuluh keunggulan demokrasi dibandingkan dengan sistem lain yang tidak demokratis, yaitu (1) menghindari tirani; (2) Hak-Hak Asasi; (3) Kebebasan Umum; (4) Menentukan nasib sendiri; (5) Otonomi moral; (6) Perkembangan manusia; (7) Menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) Persamaan politik; (9) Mencari pedamaian; dan (10) Kemakmuran,” (xxxiv).
Prof. Lili juga memaparkan beberapa keunggulan lainnya. Namun, pertanyaannya keunggulan apa saja dari teori tersebut yang telah berhasil kita capai? Di sinilah letak sumbangsih berharga DJM dalam berupaya membuka mata kita menyaksikan bagaimana kekuasaan bekerja menggergaji demokrasi.
Penyalahgunaan kekuasaan tersebut, sialnya, justeru berlangsung di tengah pandemi. Saat rakyat tak berdaya. Kondisi kita pun bak peribahasa, “Sudah jatuh, tertimpa tangga”. Digigit anjing pula!
Buku ini juga merupakan sebuah upaya untuk menemukan jawaban atas keresahan Dadang Juliantara pada epilognya, “Demokrasi: Masihkah Ada Harapan?”. Melalui bunga rampai setebal 511 halaman ini, kita akan dapat merasakan getaran kesetiaan DJM merawat harapan bagi perbaikan demokrasi dengan cara yang belakangan ini kerap membuat Penguasa alergi: kritik.
Reses virtual
Kegundahan DJM yang ia uraikan pada buku ini sejatinya berangkat dari akumulasi suara rakyat. Bukan semata serangkaian teori dan konsep yang tak menjejak. Melainkan kompilasi kegelisahan anak bangsa yang berpijak pada realitas sehari-hari di Indonesia.
Ia merentang mulai dari hilangnya kekuatan penyeimbang negara dan oposisi, terjadinya praktik korupsi politik, peran masyarakat sipil yang lemah, rendahnya efektivitas pemerintahan, sekaratnya KPK, menguatnya ancaman kebebasan berbicara, morat-marit kebijakan PPKM, adanya kekebalan hukum terhadap para pendukung Penguasa, ketimpangan ekonomi, hingga teror dunia maya terhadap kelompok kritis.
Alhasil, buku ini tak ubahnya hasil kerja resap aspirasi (reses) secara virtual DJM sebagai Anggota DPR RI. Ia merekam opini publik yang berasal dari berbagai media online serta percakapan netizen yang tengah menumpahkan keresahannya tentang kondisi negara belakangan ini.
Pada hampir seluruh tulisan, DJM banyak menyebut nama-nama figur publik berikut aspirasinya, terutama dalam kaitan mereka sebagai korban ketidakadilan dan pembungkaman suara oleh penguasa. Mulai dari publik figur, hingga rakyat jelata.
Nama-nama tersebut di antaranya, Alissa Wahid, Dandhy Dwi Laksono, Rocky Gerung, Ananda Badudu, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, hingga Bintang Emon. Hal ini terutama dapat kita temukan pada tulisan berjudul, “Hayo, Kritiklah Daku, Kau Kutangkap!” (h.178).
Pantauan DJM terhadap aspirasi rakyat di jagat medsos rupanya juga terarah kepada generasi muda yang juga turut merasakan keresahan di bawah rezim hari ini. Nama yang disebutkan terakhir di atas merupakan contoh korban saja bagaimana rezim begitu bergairah membungkam rakyat. Pembungkaman bukan saja oleh aparat di dunia nyata, tapi juga pasukan buzzer di jagat maya.
“Salah satu kasus paling menyita perhatian terjadi pada pertengahan 2020 lalu yang menimpa seorang anak muda. Saat itu, komika Bintang Emon mengomentari vonis rendah terhadap penyerang Novel Baswedan penyidik senior KPK. Usai komentar itu viral, Bintang mulai dihujat akun anonim yang sangat banyak jumlahnya. Puncaknya, para buzzer memainan isu bahwa Bintang Emon adalah pecandu narkoba. Serangan-serangan ini telah membuat Bintang Emon kelabakan sampai-sampai ia harus menjawabnya dengan menunjukkan hasil tes urine untuk meyakinkannya,” tulis DJM (h.183).
Penguasa kini masih terus memburu suara-suara kritis. Namun, generasi muda juga tetap gigih mengungkapkan suara mereka secara kreatif. Misalnya, melalui video pendek, poster digital dan mural di dinding-dinding terbuka di berbagai kota di Indonesia. Betapa menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada hari-hari ini merupakan hal yang berbahaya. Tepatlah kiranya artikel DJM berjudul, “23 Tahun Reformasi, Arus Balik Penegakan Hukum ala Orba Telah Kembali” (h.275).
Mengganggu penguasa
Buku ini ditulis dalam rangka merawat akal sehat publik dari cengkraman hegemoni pemegang kekuasaan. Hal ini begitu gamblang tergambar pada tulisan DJM berjudul, “Pentingnya Menjaga Letupan Suara yang Membuat Gerah Penguasa” (h.135).
Seluruh bagian dari buku ditulis secara ringan dan menarik. DJM biasanya mengawali dengan pengantar sederhana, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar atas isu yang sedang ia bahas. Pada bagian pertengahan pembahasan, kita pun akan diajak menelusuri kesenjangan antara ‘apa yang terjadi’ dan ‘apa yang seharusnya’.
Tepat pada momen penelusuran itulah, kita akan merasakan kegundahan sekaligus semacam kejengkelan DJM atas perilaku Penguasa yang kurang berpihak pada kepentingan publik. Ditambah lagi, tumpulnya peran anggota legislatif. Situasi semacam ini digambarkan secara lirih pada artikel berjudul “’Perselingkuhan’ Itu Membuat Sunyi Gedung Wakil Rakyat” (h.310).
Jika kita ringkas ke dalam satu kalimat, maka buku ini tak ubanhnya merupakan perwujudan dari diktum Lord Acton yang sangat terkenal itu: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).
Dua bagian terakhir dari buku ini kiranya dengan baik menjabarkan diktum tersebut, yakni Bagian Lima, “Sekaratnya KPK di Tangan Penguasa”, dan Bagian Enam, “Wajah Suram Aparat Kepolisian”. Sebagai kumpulan tulisan, pembaca tidak harus membacanya dari awal halaman. Pembaca dapat menentukan sendiri bagian mana yang perlu dibaca duluan. Sesuai keperluan.
Soldier-scholar
22 Agustus lalu, harian Kompas menurunkan laporan pada rubrik politik dan hukum berjudul “Politisi dan Kebiasaan Membaca Buku”. Diwartakan bahwa beberapa partai politik besar di Indonesia mengadakan sekolah politik khusus yang bercorak intelektual untuk kadernya. Beberapa buku tertentu pun menjadi bacaan wajib kader. Hal itu guna meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual kepartaian. Bahkan, mereka menerbitkan buku-buku untuk dibagikan ke daerah.
Bila kita menilik sejarah bagaimana republik ini berdiri, para Pendiri Bangsa memang begitu mengakrabi buku. Buku bukan belaka untuk mengisi waktu senggang, tapi sebagai panduan dan inspirasi perjuangan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, para pendiri bangsa sadar betul akan posisi kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang oleh sebab itu mereka pun menetapkan salah satu misi negara ini adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Terbitnya buku ini kiranya merupakan upaya DJM menapak tilas para Pendiri Bangsa. Selain sebagai elite politik, para pendiri bangsa sejatinya merupakan elite intelektual yang membasiskan perjuangan mereka pada keagungan literasi.
Selama di Senayan, DJM sendiri telah menerbitkan “Presiden Offside: Kita Diam atau Memakzulkan” (2012), “Menggugat Logika APBN: Politik Anggaran Partai Gerindra di Badan Anggaran DPR RI” (2012), “DPR Offside: Otokritik Parlemen Indonesia” (2013), “Menatap Masa Depan Indonesia” (2015), “Fungsi-Fungsi DPR: Teks, Sejarah, dan Kritik” (2020), dan “Prahara Demokrasi di Tengah Pandemi” (2020).
Sebagai anggota DPR sekaligus pimpinan Partai Gerindra, apresiasi DJM terhadap literasi kiranya amatlah menarik jika ia terinternalisasi secara formal di dalam partainya dalam rangka melahirkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan bangsa dan negara. Kombinasi antara semangat patriotik-militeristik ala Prabowo Subianto dengan ketajaman kritisisme-aktivisme DJM, kiranya akan melahirkan apa disebut ‘soldier-scholar’ oleh Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo ketika ia menulis sebuah buku tentang Jepang berjudul, “Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjoeangan Hidup”.
Saat menjadi Dubes di Jepang, Sayidiman meriset bagaimana proses modernisasi di sana berlangsung. Ia menemukan satu hal menarik dalam tradisi dunia militer Jepang yang ia sebut soldier-scholar. Mereka adalah pemegang teguh kode etik Bushido, yang beralih menjadi anggota militer. Di kemudian hari, tidak sedikit dari mereka duduk pada posisi-posisi strategis yang melahirkan kebijakan-kebijakan publik.
Konsep soldier-scholar, menurut Sayidiman, lebih dekat dengan konsep “ksatria”, dan berbeda dari para pejuang militer Eropa (knight, ridder). Soldier-scholar bukan semata pasukan yang hanya tahu cara mengangkat senjata, tapi juga punya ketajaman pikiran dan kehalusan perasaan yang memampukan mereka mencengkramai kedalaman ilmu pengetahuan dan mencumbu keelokan seni dan sastra. Model soldier-scholar tersebut bahkan melakukan meditasi untuk mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi.
“Sampai pada Perang Dunia II, perwira Angkatan Perang Jepang yang tampaknya keras dan kejam itu, kebanyakan juga mengejar kepandaian untuk membuat pantun (haiku) yang bermutu tinggi. Karena sifat-sifat samurai ini, maka banyak ahli ilmu pengetahuan Jepang berasal dari samurai. Konsep ‘soldier-scholar’ yang begitu langka ditemukan dalam dunia keprajuritan Barat, di Jepang merupakan hal biasa,” tulis Sayidiman di halaman 50 pada buku terbitan 1987 oleh Penerbit UI.
Kompilasi keresahan
Buku ini kiranya dapat menjadi lebih tipis jika tim editor menghindari pengulangan. Pasalnya, terdapat beberapa artikel yang sudah pernah diterbitkan pada karya DJM sebelumnya, yakni artikel “Mempertanyakan Konsistensi Hukum Protokol Kesehatan” (h.199), “Salah Kaprah Penerapan Azaz Keselamatan Rakyat Ialah Hukum Tertinggi.” (h.220), “Menelisik Calon Kapolri Baru Pilihan Istana” (h.401).
Selain pengulangan beberapa artikel, judul buku ini agaknya cukup ambigu. Kalimat ‘Kekuasaan Biang Kerok Perusak Demokrasi’ mengandaikan relasi antagonistik yang saling menafikan antara kekuasaan dan demokrasi. Demokrasi adalah ruang bagi keduanya. Dengan kata lain, kekuasaan tidak melulu perusak demokrasi.
Struktur kalimat judul menyederhanakan fakta bahwa jenis kekuasaan pada tubuh demokrasi tidak tunggal. Penyederhanaan yang tentu saja menimbulkan tanda tanya. Tapi, prolog Prof. Lili Romli kiranya telah menjelaskan ihwal ini dengan baik, bahwa kekuasaan memang dapat menjadi destruktif ataupun konstruktif bagi demokrasi.
Beberapa hal teknis cetakan pertama terbitan Law-Justice (Portal Berita dan Investigasi) ini masih menyisakan beberapa catatan, terutama karena bertabur kesalahanketik (typo) dan inkonsistensi penggunaan pungtuasi. Tapi, tentu saja ihwal tersebut tidak mengurangi substansi dari persoalan yang dibahas. Hanya saja, oleh sebagian orang, urusan teknis begini biasanya memang dijadikan kadar keseriusan sebuah karya tulis. Apalagi ia kelak akan menjadi abadi bagi generasi selanjutnya.
Isu memburuknya demokrasi selama pandemi ini memang kian meresahkan publik. Berbagai pihak telah meresponinya. Misalnya, 2020 lalu, LBH Jakarta menerbitkan buku “Demokrasi di Tengah Oligarki dan Pandemi”. Agustus 2021 ini, terbit juga sebuah buku hasil keprihatinan ratusan ilmuwan sosial politik terhadap anjloknya demokrasi kita. Mereka beramai-ramai menulis “Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia”.
Apakah kegelisahan publik itu tidak sampai ke telinga elite? Di sinilah kita akan menemukan kekuatan buku DJM. Kritik DJM sebagai ‘orang dalam’ Senayan menghadirkan nuansa berbeda dari perspektif pengamat belaka. Ini tentunya juga kabar gembira bahwa rupanya masih ada anggota DPR kita yang dengan sangat baik telah menangkap suara rakyat yang tengah dibungkam.
Namun, persis pada sikap seperti ini, akibat menyuarakan suara rakyat, DJM pun seperti menjadi anomali, asing dan tidak populer di tengah hiruk pikuk konsolidasi elite Pemerintah, DPR serta penegak hukum bergotong royong mewajarkan pembusukan demokrasi. Melalui buku ini, DJM memilih menjadi ‘sang burung pipit’.