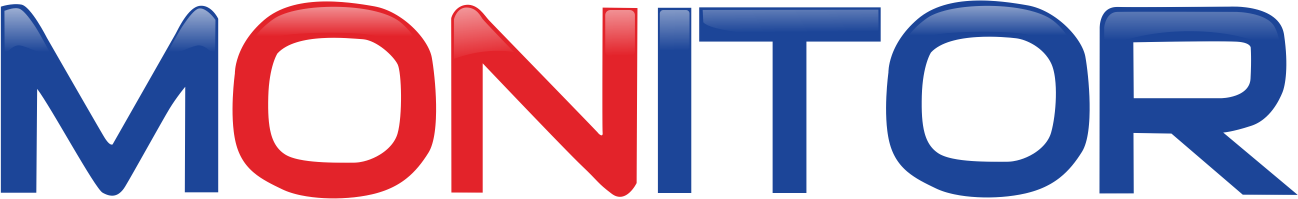MONITOR, Jakarta – Minggu, 14 Juli 2019, Al Maliki Center, sebuah lembaga yang diasuh oleh Kyai muda NU, Muhammad Aqib Malik, bergerak di bidang pemberdayaan SDM, menyelenggarakan diskusi bertajuk “membincang pendidikan alternatif, belajar dari komunitas belajar Qoryah Thayibah”.
Qoryah Thayibah merupakan komunitas belajar yang lahir atas inisiasi gerakan serikat tani di Desa Kalibening, Salatiga. Kehadirannya ingin menjawab kebuntuan di tengah sistem pendidikan kita yang rigid.
Dalam diskusi itu, Ziaul Haq, pendamping belajar di komunitas itu bercerita, semula Qoryah Thayibah adalah SMP terbuka yang menyelanggarakan pendidikan formal. Keberadaannya diharapkan mampu dijangkau oleh para petani kecil yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya karena minimnya biaya.
Di awal kiprahnya, tahun 2003, SMP terbuka Qoryah Thayibah sudah melakukan praktik belajar yang berbeda, berdasarkan prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan, belajar disandingkan langsung dengan berkarya. Kreativitas anak menjadi pijakan dalam pembelajaran. ” Suasana belajar haruslah ruang ekspresif dan gembira bagi para siswa” ujar Ziaul Haq.
Tahun 2006, Bahrudin, penggagas utama komunitas belajar ini, memutuskan tidak lagi menyelenggarakan sekolah formal. Hal ini disebabkan di antaranya karena kurikulum pendidikan formal kerapkali membatasi ruang aktualisasi diri. SMP terbuka Qoryah Thayibah pun berubah menjadi lembaga pendidikan non formal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan nama Komunitas Belajar Qoryah Thayibah (KBQT).
Pada fase ini, penyelenggaraan pendidikan di komunitas belajar Qoryah Thayibah benar-benar mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak ada mata pelajaran, objek yang dipelajari bisa apa saja yang menjadi kesepakatan bersama para murid. Tidak ada guru, yang menemani belajar siswa adalah pendamping belajar. Evaluasi pembelajaran berdasarkan karya yang ditampilkan, mereka menarasikan apa yang dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. “Intinya sekolah sing digawe gampang (intinya sekolah yang dibuat mudah)” pungkas Ziaul Haq, pendamping belajar di KBQT yang berasal dari Tegal.
Di komunitas belajar ini, anak-anak terbiasa berdiskusi, bermusyawarah tentang berbagai hal terkait suasana belajar dan juga objek pembelajaran. Pendamping belajar bukan menjadi sumber belajar. Mereka merupakan fasilitator yang membantu mengarahkan riset yang dilakukan anak-anak. Membuat narasi dan melakukan presentasi menjadi menu belajar sehari-hari di komunitas ini.
Di KBQT, belajar selalu bertolak dari realita. Misal, Ziaul Haq bercerita bahwa dirinya mendampingi anak-anak mengunjungi pasar. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Begitu waktu yang telah disepakati selesai, anak-anak berkumpul kembali di tempat semula. Mereka mengadakan diskusi dan terkumpullah beberapa artikel yang membahas seputar permasalahan yang mereka temui, seperti tempat-tempat yang kumuh, parkiran yang tidak layak, mudahnya akses dan lain-lain.
Mendengar pemaparan itu semua, saya seperti melihat kembali Taman Siswa yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara. Berpegang pada prinsip yang beliau sebut sebagai pancadharma, yaitu: kemanusiaan, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan dan kodrat alam.
Ruang belajar sekolah formal
Nampaknya, model belajar yang dipraktikan di komunitas belajar Qoryah Thayibah absen dari sekolah-sekolah formal. Ruang belajar di sekolah formal kerap kali disesaki oleh aktivitas yang melulu terkait capaian akademik.
Kurikulum memang terus berganti, seolah berjalan dinamis seturut dengan perubahan jaman. Nyatanya, para pelaku pendidikan di dalamnya belum cukup mampu menerjemahkan praktik pendidikan yg didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan.
Turut sebagai pembicara, saya menyampaikan bahwa pelajaran tematik masih dipahami secara parsial. Guru sebagai sutradara dan skenario pembelajaran mestinya merancang kegiatan, bukan materi. Aktivitas yang dirancang adalah aktivitas yang anak-anak sukai atau berbasis pada masalah yang dekat dengan anak. Dari situ anak diminta mengamati, berdiskusi, dan mencari solusi. Jadi, anak-anak fokus pada masalah dan pemecahannya, tidak perlu mengidentifikasi ini pelajaran apa.
Kurikulum 2013 sebenarnya mengakomodir model belajar semacam itu. Otonomi pendidikan yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa semestinya memunculkan warna-warni hasil pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah dan menampilkan keunggulan-keunggulan yang sesuai dengan kekhasan yang dikembangkan. Sayang, sekolah formal meluluskan siswa yang kemampuannya hampir seragam.
Hasil tes PISA tahun 2015 menguatkan itu. Anak-anak Indonesia berada di tangga terendah dalam kemampuan membaca, matematika dan sains. Ketika diluncurkan tes Indonesia National Assessment Programm (INAP) oleh Kemendikbud, hasilnya belum beranjak baik. Lebih dari 70% peserta didik kita gagal dalam bidang matematika dan sains. Hampir 50% lemah dalam membaca.
Ibarat olahraga beladiri, anak-anak kita tidak memiliki kuda-kuda yg kokoh. Penilaian oleh INAP itu mengisyaratkan bahwa ke depan, dalam bahasanya Rheinald Kasali, anak-anak kita ibarat buah strawberry, tampak merah, menyala semangat, namun sesungguhnya mudah terluka, rapuh, gampang mengalah dan memilih zona nyaman.
Keresahan masyarakat
Dalam diskusi itu, pertanyaan dan tanggapan peserta membuat saya prihatin. Betapa sebenarnya masyarakat pun resah dengan model belajar yang diterapkan di sekolah formal. Beban mata pelajaran yang banyak, PR yang hampir setiap hari dan tugas yang hanya tuntutan formalitas berbuah kelelahan fisik dan psikis pada anak. Belajar bukan lagi aktivitas yang menyenangkan.
Alhasil, sekolah formal sudah selayaknya berbenah. Belajar dari Komunitas Belajar Qoryah Thayibah, sekolah formal sudah seharusnya mampu mengadaptasi model belajar yang ekspresif, menggembirakan dan menghasilkan karya berbudaya.