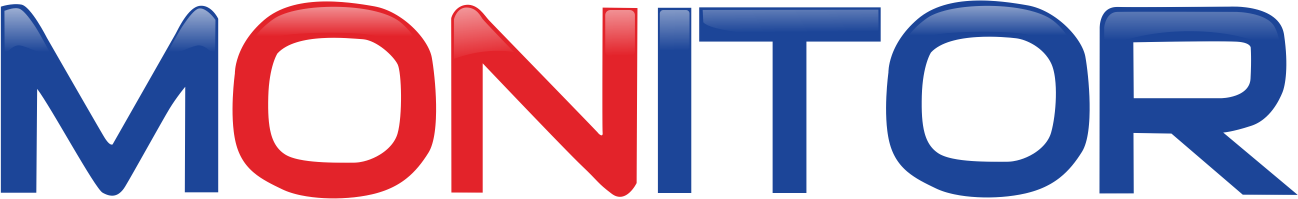Oleh: Divisi Riset Pusat Kajian Keuangan Negara
Selama dua tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat masih mencari formula yang tepat untuk menjejakkan Nawacita ke dalam politik anggaran serta kebijakan pembangunan.
Sejarah mencatat, setiap presiden membawa ideologi (belief on goodness) ekonominya masing-masing. Presiden Sukarno mengusung Ekonomi Gotong Royong. Presiden pertama Indonesia tersebut juga mencetuskan ajaran Trisakti. Kemudian saat Presiden Suharto memimpin, pemerintah mempopulerkan jargon Ekonomi Pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Selanjutnya di era reformasi, ideologi ekonomi Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati nampak masih samar, karena konsentrasi era pemerintahan ini lebih condong pada konsolidasi kebangsaan. Kemudian, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi orang nomor satu di negeri ini, dia memperkenalkan apa yang disebut SBYnomics yang terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu pro growth, pro job, dan pro poor.
Sementara itu, Presiden Jokowi tampil di panggung kekuasaan hasil Pemilu Presiden tahun 2014 dan mengusung ideologi Jokowinomics. Adapun, Jokowinomics tersebut dapat dibaca melalui Nawacita atau sembilan program yang menjadi agenda prioritas pemerintah periode 2014-2019.
Bagaimana strategi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam menerjemahkan Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan?
Problem Perencanaan Nasional
Sebelum menilai pencapaian Nawacita selama dua tahun ini, ada baiknya kita mendiskusikan kembali perencanaan nasional sebagai legitimasi formal kenegaraan. Secara teoritis, menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
Dari definisi tersebut, diketahui perencanaan nasional sangat penting sebagai indikator pencapaian tujuan dalam rentang waktu tertentu. Dalam konteks pembangunan nasional, Indonesia memiliki jejak sejarah pola perencanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Sebagai contoh, di era Presiden Soekarno pemerintah menerapkan Pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Kemudian di era Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dasar perencanaan nasional.
Pada aspek Pola PNSB tahap pertama (1961-1969) sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No II/MPRS/1960, aspek pembangunan yang diatur juga berkaitan dengan aspek-aspek fundamental. Pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga termasuk pembangunan revolusi mental dalam membangun karakter kebangsaan manusia Indonesia seutuhnya.
Sementara, GBHN era Presiden Soeharto—meskipun sama-sama ditetapkan oleh MPR seperti PNSB—ruang lingkupnya hanya berisi haluan pembangunan pemerintahan pusat yang dilaksanakan oleh eksekutif saja. Sedangkan orientasi aspek pembangunan GBHN terlalu menitikberatkan kepada aspek pembangunan fisik. Sementara itu, aspek pembangunan karakter nasional bangsa banyak diabaikan.
Selanjutnya pada era reformasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pola perencanaan ini terbagi dibreakdown ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Bila dibandingkan dengan kedua sistem perencanaan di era sebelumnya, SPPN dibuat oleh masing-masing Presiden terpilih, dan cenderung lebih eksklusif. Selain hanya mengatur haluan pemerintahan selama lima tahun—yang merupakan visi dan misi capres/cawapres—SPNN juga disusun dan diputuskan sendiri oleh pemerintah.
Berpangkal pada hal tersebut, banyak kalangan memberikan kritik terhadap SPNN yang terasa parsial dan belum mencerminkan pola pembangunan yang berkelanjutan. Saat dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2015), Bahrullah Akbar menyinggung beberapa permasalahan terkait perencanaan nasional.
Pertama, jargon perencanaan pembangunan masih bersifat seremonial, business as usual tanpa arah yang komprehensif. Artinya, perencanaan masih mengedepankan pekerjaan administratif dan seremonial, dibandingkan bagaimana membahas kualitas perencanaan dan hubungan perencanaan pusat dan daerah, yang terkorelasi dengan tujuan berbangsa bernegara. Menyedihkan untuk mengatakan 71 Tahun Indonesia belum ada blue print jangka panjang sebagai acuan tujuan berbangsa dan bernegara.
Kedua, kita tidak mempunyai dashboard Keuangan Negara berupa perhitungan sumber potensi keuangan negara atau penggalian revenue centre yang komprehensif dan integratif bagi negara. Sebagai contoh antara lain berupa potensi pajak dan cukai yang belum tergali, timpangnya kemampuan pendapatan asli daerah (retribusi) dengan dana transfer, optimalisasi sumber daya alam, seperti antara lain; leverage asset perhitungan cadangan minyak , gas bumi, minerba serta potensi kemaritiman dan hasil laut.
Ketiga, tidak adanya koordinasi dan arah yang jelas dalam penyusunan perencanaan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain tidak meet and match kepentingan pusat dan daerah dalam belanja tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
Keempat, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan yang berada di BUMN, BUMD dan BLU masih belum terjangkau dalam penyusunan perencanaan pembangunan komprehensif dan integratif.
Kelima, perencanaan strategis yang disusun selama ini masih belum mempola secara khusus pembangunan manusia Indonesia secara utuh (nation and character building). Permasalahan di atas menandakan bahwa sumber daya manusia kita belum mendapat perhatian secara khusus. Sasaran pembangunan hanya terfokus kepada pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kita belum sepenuhnya membangun jiwa dan raga secara utuh dan fundamental.
Lalu, bagaimana upaya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam memperbaiki perencanaan nasional, dan sekaligus menerjemahkan visi, misi dan janjinya ke dalam kebijakan pembangunan?
Nawacita dan RPJMN
Sekalipun perencanaan nasional kita dewasa ini dihadapkan pada problema seperti diutarakan di atas, kita melihat upaya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk melakukan perubahan-perubahan pada RPJMN 2015-2019. Sekadar mengingat, proses penyusunan RPJMN 2015-2019 telah dimulai pada Januari 2014, seiring diterbitkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang ditandatangani Armida S. Alijahbana pada 3 Januari 2014.
Di sinilah letak tantangannya. Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dikejar “deadline” untuk merumuskan kembali RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.
Walhasil, dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, yaitu tertanggal 15 Januari 2015 secara resmi pemerintah menerbitkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Begitupula dengan RKP 2015, yang disusun pada tahun 2014 oleh Pemerintahan SBY-Boediono, kemudian direvisi seiring dengan penyusunan RAPBN Perubahan 2015 yang disahkan pada tanggal 14 Februari 2015.
Banyak kritik dialamatkan pada dokumen resmi perencanaan nasional jangka menengah tersebut. Setidaknya terdapat empat model masalah yang dapat kita telisik, antara lain; pertama, indikator Nawacita dan RPJMN tidak sama. Kedua, Nawacita memiliki indikator, sedangkan RPJMN tidak punya. Ketiga, RPJMN punya indikator, sedangkan Nawa Nawacita tidak punya. Keempat, Nawacita memiliki indikator global, sedangkan RPJMN penuh dengan indikator detail tanpa ada yang global.
Sebagai contoh, Nawacita memiliki sebuah indikator untuk menjadikan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penyumbang 60 persen PDB. Sementara itu, RPJMN tidak memiliki indikator itu, hanya terdapat indikator-indikator kecil seperti UMKM mencapai 7,5 persen dari PDB, keanggotaan koperasi mencapai jumlah tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya, problem paradigmatik yang penting disorot adalah jargon Revolusi Mental yang tidak “bunyi” dalam RPJMN.
Pada mulanya, politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, juga melayangkan kritik terhadap RPJMN 2015-2019. Dia mengatakan, target Nawacita seperti penurunan gini rasio dan mal nutrisi tidak bunyi di RPJMN Teknokratis.
“Justru program MP3EI yang dominan karena rancangan RPJMN sudah disusun Februari 2014, saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," terang dia dalam Diskusi RPJMN di Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Eva menyebut, beberapa contoh kesenjangan RPJMN dan Nawacita yakni; pertama, Nawacita memberi tekanan pada misi mengurangi kesenjangan ekonomi dengan target 0,30 persen pada 2019, sedangkan RPJMN tidak memberikan perhatian pada target ini.
Kedua, Nawacita memberikan perhatian besar pada pengurangan barang impor bahan baku dan barang modal 5 persen per tahun. RPJMN tidak memberi perhatian pada target tersebut. Ketiga, Nawacita mencanangkan target rasio pajak 16 persen terhadap GDP hingga 2019, sementara RPJMN hanya menargetkan optimalisasi penerimaan negara.
Kesenjangan keempat, beberapa target bidang kesehatan RPJMN cenderung konservatif. Angka kematian ibu dan anak dalam RPJMN ditargetkan 306 per 100 ribu pada 2019. Sementara Nawacita memasang target 102.
Kelima, Nawacita memproyeksikan prevelensi bayi gizi buruk nol persen sampai lima tahun mendatang dan RPJMN hanya turun sampai 17 persen di 2019. Sementara itu, indikator dalam bidang pendidikan pun masih dalam rangka implementasi kurikulum 2013, karena hampir pasti tidak akan terlaksana oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah.
Namun belakangan, ketika dihubungi redaksi, Eva mengatakan kritiknya telah dijawab pemerintah. “Kritik itu sudah direspon, gini ratio turun sedikit. Dengan pemotongan APBN-P kita harus hati-hati. Yang krusial justru concentration of wealth yang trendnya lebih kuat,” katanya, Senin (5/9/2016).
Ambisius atau Utopis?
Apabila mendalami isi RPJMN dan dokumen Nawacita, memang masih terdapat beberapa kesenjangan antara sasaran, target dan indikator yang ditetapkan dari masing-masing dokumen.
Sebagai contoh misalnya, indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Nawacita ditetapkan 76.60, tetapi sasaran RPJMN menetapkan 76.30. Sedangkan realitas tahun 2015 sebesar 69.55. Selain itu, indeks gini ratio di Nawacita memproyeksikan 0.30, tetapi di dalam RPJMN dipatok 0.36. Dan, realitas tahun 2016 indeks gini ratio sebesar 69.55.
Kesenjangan yang juga mencolok misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, yang disasar Nawacita sebesar 6.0%-7.5%, namun di RPJMN malah dipatok lebih tinggi yaitu sebesar 8%.
Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan dipatok realtif moderat, Nawacita mencanangkan kurang dari 8%, sedangkan RPJMN mematok kisaran 7-8%. Begitupula dengan tingkat pengangguran terbuka, Nawacita menargetkan 4% dan RPJMN mematok 4-5%.
Bersandar pada acuan indikator Nawacita dan RPJMN tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nawacita belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perencanaan nasional. Padahal, indikator-indikator tersebut menjadi basis acuan penilai masyarakat terhadap pencapaian, serta janji dan visi misi Presiden Jokowi.
Karena itu, untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional, pemerintah perlu bekerja keras mengejar target-target yang ambisius tersebut, dan sekaligus mewaspadai realitas yang terjadi saat ini. Ambil contoh misalnya untuk mewujudkan IPM sebesar 76.30 tahun 2019. Berbekal pencapaian IPM tahun 2015 sebesar 69.55, maka pemerintah perlu bekerja keras menambah sekitar 1.69 point setiap tahunnya.
Adapun, pembentuk IPM terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (kualitas pendidikan), dan standar hidup layak (perekonomian). Dari ketiga dimensi tersebut, kita masih dihadapkan pada sejumlah kekhawatiran.
Dari dimensi kesehatan, kita menghadapi kekhawatiran sebagai berikut; pertama infrastruktur kesehatan belum merata dan kurang memadai. Dari sekitar 9.599 Puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besar masih berpusat di kota-kota besar. Hal ini juga berkelindan dengan tingkat ketersediaan kamar, khususnya rawat inap di rumah sakit untuk memberikan pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang kini jumlahnya telah mencapai 142 juta.
Kedua, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Data terakhir Kementerian Kesehatan RI memang mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1%-3%.
Kemudian dimensi pendidikan, kita juga dibayangi oleh berbagai permasalahan. Menurut data dari UNESCO (2015) pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Hal tersebut disebabkan karena kualitas pendidikan di Indonesia yang masih kurang baik, yang ditandai dengan rendahnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru, prestasi siswa, serta pemerataan kesempatan pendidikan.
Sementara itu dari dimensi standar hidup layak, fenomena ketimpangan pendapatan masih menjadi momok yang mewarnai 71 kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan data BPS (2016), tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia yang diukur dengan menggunakan gini ratio pada Maret 2016 mengalami perbaikan menjadi sebesar 0,397. Pencapaian tersebut mendekati batas berbahaya level ketimpangan sebesar 0,40.
Diketahui, belakangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengkaji kemungkinan adanya revisi atas RPJMN 2015-2019 yang dinilai sudah tidak realistis. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berkilah rencana tersebut dilakukan karena perencanannya waktu itu kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
“Rencana itu kan selalu awal di depan, begitu sudah berjalan kita harus review apakah yang dilakukan selama ini sudah sesuai sasaran atau belum, atau mungkin perencanannya waktu itu kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (28/7/2016). (*)