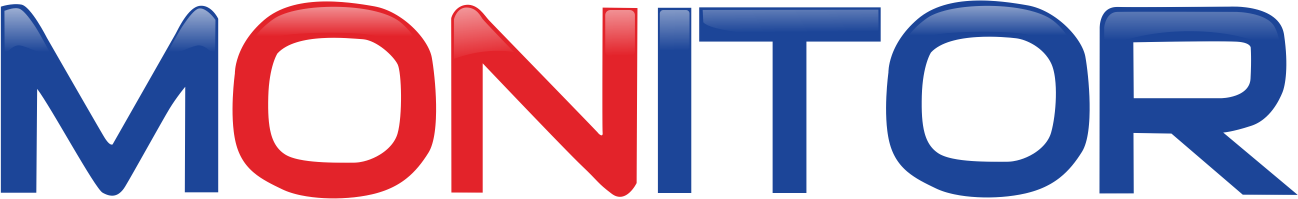MONITOR, Jakarta – Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR.
Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Kontras, Imparsial, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, dan TII memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model.
Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.
“Belakangan ini muncul keinginan TNI meminta Pansus RUU terorisme untuk mengakomodir beberapa usulan TNI, yakni pertama tentang perubahan judul Undang-Undang menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme,” ujar Direktur Perlindungan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Totok Yulianto dalam siaran pers yang dite rima MONITOR, Selasa (23/1).
Koalisi menilai, usulan-usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat. Diantaranya :
Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR, hal tersebut tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru. Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama.
Kedua, Koalisi menilai definisi terorisme yang diajukan dalam surat tersebut terlalu luas dan karet. Defenisi terorisme di dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus diartikan sebagai sebuah bentuk kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Perluasan defenisi itu terlalu luas dan karet sehingga potensial untuk disalahgunakan, dimana dengan defenisi yang multitafsir itu bukan hanya akan menyasar kepada-kelompok teroris tetapi juga potensial akan menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.
Ketiga, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme criminal justice system. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka criminal justice system. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.
Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara.
Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.
Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum.
“Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum,” ujar Totok.
DPR dan pemerintah diharapkan tidak merubah pendekatan penanggulangan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model melalui revisi UU No. 15 tahun 2003 dengan cara melibatkan militer secara aktif dalam penanganan terorisme.
Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih represif dan eksesif. Masuknya aparat non-judicial (militer) ke dalam penegakann hukum dalam mengatasi ancaman terorisme akan berdampak pada rusaknya tatanan sistem negara hukum.
Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.
Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.
Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal yang “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).
“Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip due process of law,” tegas Totok.
Atas dasar hal tersebut diatas, Koalisi mendesak kepada DPR dan pemerintah agar :
- Pembahasan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka model penegakan hukum (criminal justice system model) dan jangan bergeser ke arah war model.
- Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM
- Revisi UU No. 15 Tahun 2003 perlu memperkuat tata nilai HAM di dalamnya demi memastikan arah penegakan hukum dalam mengatasi terorisme yang menghormati HAM.
- Memperbaiki dan merubah pasal-pasal dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sekiranya dapat mengancam penegakan HAM sebagaimana dimaksud di atas.
- Revisi UU No. 15 Tahun 2003 harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjamin keamanan (security) masyarakat di satu sisi dengan keharusan negara untuk tetap melindungi dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara (liberty) di sisi lain.